
Langit mendung menggelayut di atas atap rumah kecil milik keluarga
Ratih. Kala itu bendera kuning di ujung jalan tertulis nama Ibrahim,
suami Ratih. Jelas ada raut duka yang Ratih samarkan dengan senyuman.
Sosoknya tetap kuat berdiri sambil menggendong si kecil dan menerima
salam duka cita dari sanak keluarga, sahabat dan para tetangga yang
berdatangan.
Ratih adalah sahabat SMA ku yang sudah tak jumpa
beberapa tahun lamanya. Ketabahan dan keikhlasannya masih seperti dulu,
jilbab panjang dan kaus kaki menandakan keistiqomahannya. Rutinitasnya
selama ini tidak jauh seputar dakwah, sebagai guru TK disebuah TK kecil
sederhana dan menjadi guru ngaji yang rutin digelutinya setiap hari.
Kini,
tidak ada lagi suami di sisi, tempat berbagi tugas mengasuh lima anak
mereka yang masih kecil. Rumah kontrakan petak itu tetap ditempatinya
bersama lima buah hati. Tidak ada harta warisan sepeninggal suami, hanya
kenangan kebersamaan di setiap sudut ruang yang lusuh. Alunan suara
merdu sang suami mengaji seolah bergema melalui pori-pori dinding bercat
pudar. Tubuh ringkih sang suami masih melekat erat di benak Ratih.
Tubuh menahan rasa sakit yang sangat dan jarang dihiraukan, hingga
tibalah waktunya sepulang shalat jumat, tubuh itu tersungkur dan mata
yang terpejam untuk selamanya.
Ooh…Ratih, begitu awamkah dirimu
tentang penyakit TBC yang merenggut nyawa suamimu, atau kondisi keuangan
yang nyaris selalu kurang membuat engkau paranoid untuk mendatangi
pelayanan kesehatan?! Tidak adakah informasi yang cukup untuk sampai ke
telingamu serta cara pengobatannya?! Kadang aku gemas dengan
kepasrahanmu, kuman TBC itu harus diberantas dengan pengobatan rutin
yang panjang dan tak akan hilang dengan obat tradisional atau herbal
seadanya. Tidak tahukah kau, pohon besar nan rindang di depan rumah
kontrakan itu menghalangi cahaya matahari masuk untuk mematikan kuman
itu, dan bagaimana dengan dirimu dan anak-anakmu, tertular penyakit
itukah?
Syukurlah, atas uluran tangan beberapa sahabat, pemeriksaan
screening TBC dapat dilakukan. Ratih sehat dan hanya ada satu anak tertular TBC. Hal itu menyadarkannya untuk
update
informasi kesehatan, dan membuka mata tentang perkembangan dunia
kesehatan. Perjuangan Ratih pun dimulai untuk memberikan obat setiap
hari untuk anaknya, karena itu tidak mudah, butuh bujuk rayu dan segala
cara agar obat pahit itu dapat tertelan demi kesembuhan anaknya.
Ah,
kesabaran Ratih sudah tidak diragukan. Aku sangat yakin atas segala
perjuangannya, seperti keyakinan kuat Ratih menghadapi masa depan
bersama kelima buah hati. Walau sulit untuk diukur dengan akal nalar,
bagaimana pundi-pundi dapat terkumpul untuk menghidupi enam kepala.
Apalagi kenaikan BBM disertai kenaikan kebutuhan pokok dan transportasi
kali ini, tentu mempengaruhi daya beli bagi keluarga seperti Ratih.
Hari
berganti, Ratih membuktikan diri mampu berperan sebagai kepala rumah
tangga tanpa meminta belas kasih sedikitpun pada setiap orang. Ratih tak
larut kesedihan, pikiran positif terhadap masa depan menjadi modal
utama untuk melangkah dan membantunya agar tetap tegar. Hal tersebut
tidak mudah bagi seorang perempuan yang cenderung ketakutan akan
kesendirian. Segala upaya dan usaha dibangun dan dikerjakan dengan
kesungguhan, kerja – kerja dakwah tetap dijalankan dan tak berkurang
porsinya. Semangat itu berkobar bukan semata desakan sebagai tulang
punggung keluarga atau status barunya, melainkan kesadaran diri Ratih
untuk menerapkan ayat alquran dalam surat Al-Ra’ad: 11 ini :
“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”
Senyum Ratih
selalu mengembang tatkala para sahabat sesekali datang menjenguk kadang
merasa prihatin menyaksikan kehidupannya, ucapan “La tahzan inallaha
ma’ana” pun sering didengungkan oleh ummahat satu ini dan menganggap
bahwa kesulitan yang tampak kasat mata itu belum sebanding dengan
kesulitan ummahat lainnya di belahan dunia manapun.








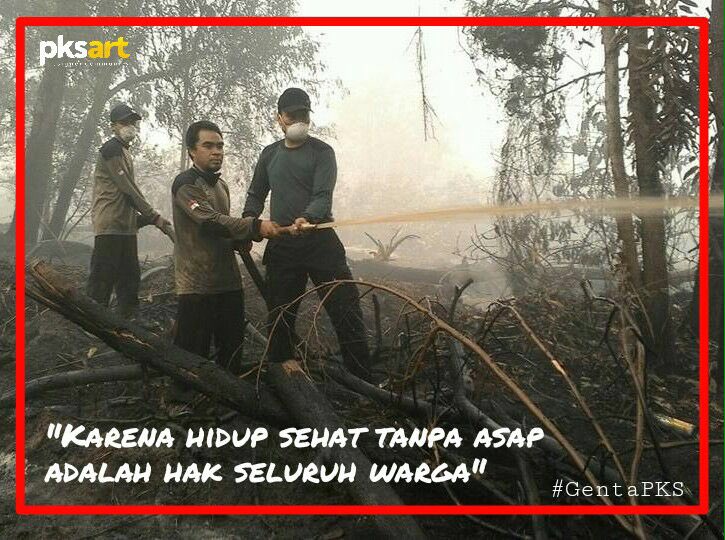















 Indonesia Time
Indonesia Time

